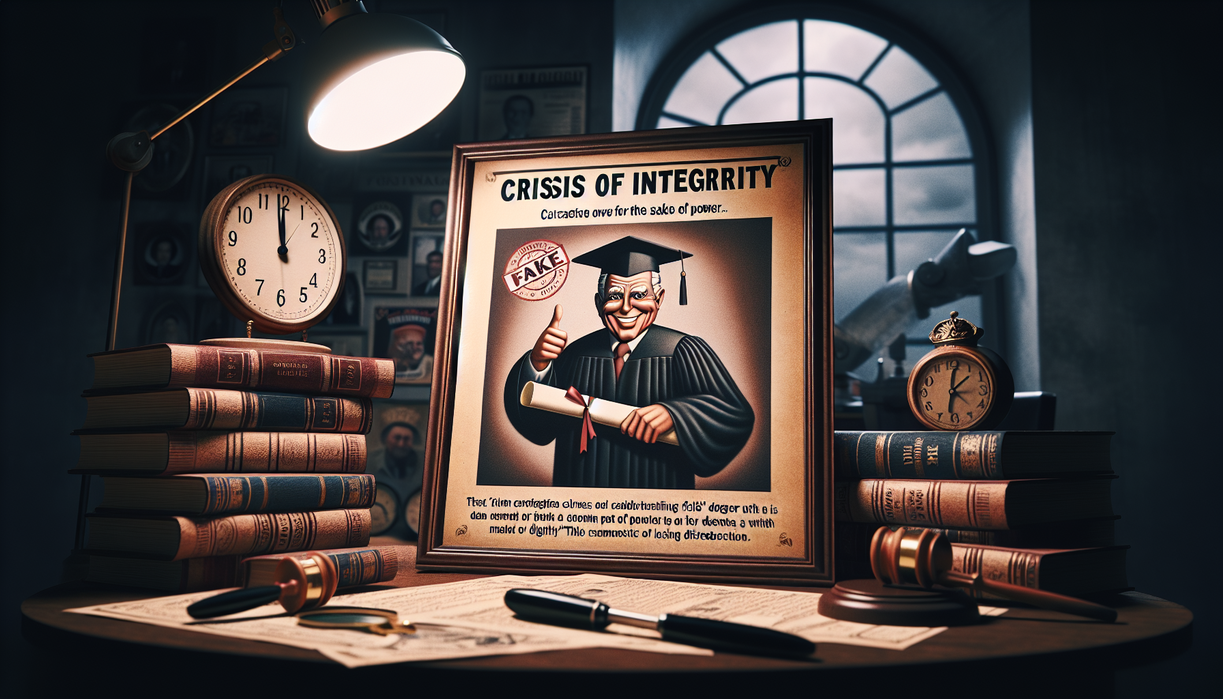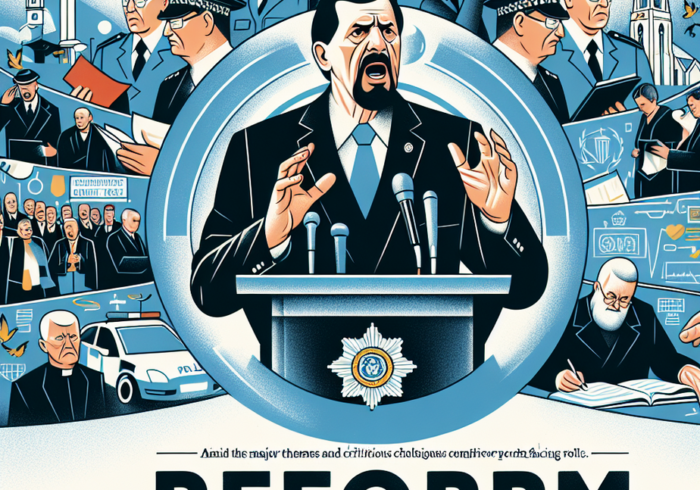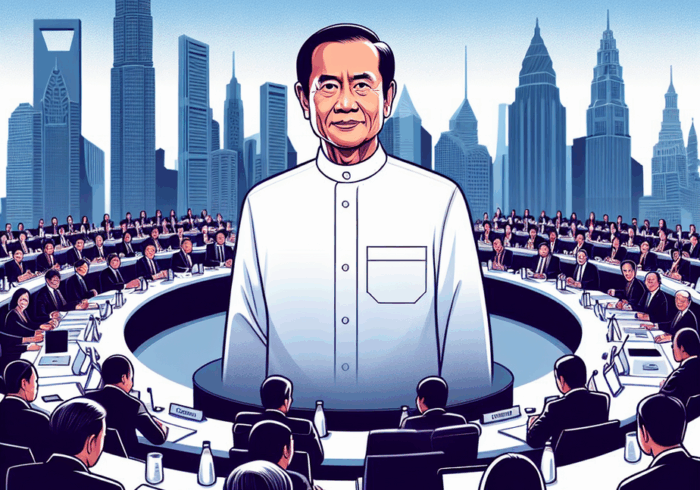www.outspoke.io – Perdebatan politik di Jakarta kembali memanas setelah Bestari Barus, Ketua DPP PSI untuk bidang politik, melontarkan kritik tajam pada isu ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo. Bukan sekadar membela, ia justru membandingkan posisi Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono, seolah ingin menegaskan bahwa serangan terhadap legitimasi pemimpin bukan hal baru di panggung politik nasional. Isu ijazah ini akhirnya melebar ke perdebatan besar soal etika, nalar sehat, serta kualitas demokrasi.
Peristiwa tersebut menunjukkan betapa kerasnya dinamika politik Indonesia. Alih-alih fokus pada gagasan besar, ruang publik sering dipenuhi kecurigaan administratif, isu personal, hingga narasi konspiratif. Bestari Barus menilai serangan itu berlebihan serta menyinggung kubu Demokrat secara pedas. Ia menyiratkan bahwa bila Jokowi diragukan lewat isu ijazah, maka SBY pun dapat diposisikan setara sebagai target delegitimasi. Dari sini terlihat, politik kita seolah terjebak dalam lingkaran saling menjatuhkan tanpa ujung.
Politik Ijazah: Simbol Krisis Kepercayaan Publik
Isu ijazah palsu bukan fenomena tunggal, melainkan gejala krisis kepercayaan terhadap institusi politik. Ketika publik mudah percaya isu semacam ini, itu menandakan rapuhnya rasa percaya terhadap proses formal negara, mulai dari administrasi pendidikan hingga mekanisme verifikasi calon pemimpin. Di era informasi cepat, kabar belum tentu benar sudah telanjur membentuk opini, lalu dimanfaatkan sebagai senjata politik. Di titik inilah komentar Bestari Barus menjadi relevan, karena ia menyoroti pola serangan yang berulang.
Pernyataan Bestari Barus sebenarnya mengandung pesan sinis terhadap praktik politik yang mengutamakan sensasi. Menurutnya, bila standar kecurigaan diterapkan ekstrem, hampir setiap tokoh bisa diseret ke pusaran tuduhan serupa. Bandingannya terhadap SBY mencerminkan ironi tersebut. Ia ingin menegaskan bahwa menggoyang legitimasi presiden lewat isu ijazah tidak hanya merugikan sosok tertentu, tetapi juga merusak wibawa institusi kepresidenan. Dalam jangka panjang, itu menciptakan preseden buruk bagi tradisi politik Indonesia.
Dari sudut pandang penulis, fenomena ini mencerminkan kegagalan elite politik untuk menawarkan debat substansial. Ketika sulit menang pada pertarungan gagasan, sebagian aktor tergoda memukul titik paling lemah: integritas personal. Kampanye politik seharusnya menguji rekam jejak, visi kebijakan, serta konsistensi pemimpin. Namun realitas justru memperlihatkan obsesi pada ijazah, foto lama, hingga isu privat. Akibatnya, kualitas demokrasi menurun, sementara publik kian lelah menyaksikan drama tanpa solusi.
PSI, Demokrat, dan Pertarungan Narasi Politik
Respons keras Bestari Barus terhadap Demokrat juga memperlihatkan bagaimana partai politik saling berebut narasi. PSI berusaha memosisikan diri sebagai pembela rasionalitas politik sekaligus pendukung Jokowi yang militan. Sikap tersebut dipakai untuk menancapkan citra: partai muda, progresif, namun berani menyerang balik ketika sekutu mereka diserang. Demokrat, di sisi lain, berupaya menjaga relevansi setelah tidak lagi memegang kekuasaan eksekutif. Pertarungan narasi itu kemudian meluas ke ruang digital, tempat opini publik mudah terbentuk.
Bila dicermati, konflik ini bukan sekadar soal ijazah, melainkan perebutan posisi moral. Setiap partai ingin tampak sebagai pihak paling benar serta paling peduli terhadap kejujuran politik. Ironisnya, cara yang dipakai justru sering memperkeruh suasana. Saling sindir, insinuasi, sampai tuduhan terselubung kerap menghiasi pernyataan publik. Padahal, tugas partai jauh lebih besar: mendidik warga, mengembangkan kader, merumuskan kebijakan. Di tengah hiruk-pikuk ini, pesan esensial politik sebagai alat kesejahteraan publik nyaris tenggelam.
Pertarungan narasi juga menunjukkan kekuatan persepsi di era politik media sosial. Satu kalimat tajam dari tokoh partai bisa viral, lalu diberi berbagai tafsir oleh pendukung maupun lawan. Bestari Barus memanfaatkan logika perbandingan antara Jokowi dan SBY untuk menohok balik pihak yang mempersoalkan ijazah. Strategi itu cerdas dari sisi komunikasi politik karena memaksa publik bertanya: bila Jokowi dipersoalkan, mengapa presiden sebelumnya tidak? Namun strategi semacam ini tetap menyisakan pertanyaan etis: sampai sejauh mana wajar memakai logika sarkastik untuk memukul balik lawan?
Mencari Politik Sehat di Tengah Badai Kecurigaan
Pada akhirnya, isu ijazah palsu, sindiran pedas Bestari Barus, serta reaksi Demokrat hanya bagian dari cerita lebih besar tentang politik Indonesia yang masih mencari bentuk dewasa. Penulis meyakini, politik sehat membutuhkan standar baru: verifikasi fakta yang ketat, partai yang berani mengakui kekeliruan, serta publik yang kritis namun tidak mudah digerakkan kebencian. Serangan terhadap legitimasi presiden seharusnya ditempatkan pada koridor bukti, bukan sekadar spekulasi. Bila elite terus memelihara politik kecurigaan, keletihan kolektif masyarakat akan kian menguat, lalu kepercayaan terhadap demokrasi bisa runtuh pelan-pelan. Refleksi terhadap peristiwa ini mestinya mendorong kita menuntut kualitas percakapan publik yang lebih bermutu, bukan sekadar lebih bising.